Assalamualaikum wr.wb
Perkenalkan nama saya udin di brebes, saya mau tanya:
1. Mana yang lebih baik bagi seorang ma'mum ketika imam sedang membaca surat al-Fatihah antara diam mendengarkan imam atau membaca doa iftitah?
2. Yang saya tahu ada beberapa ibadah seperti puasa ramadhan, haji, dsb dapat melebur semua dosa manusia yang menjalankan ibadah tersebut. Jika orang tersebut pernah tidak shalat / puasa selama 3 tahun apakah dosanya ikut kehapus juga? Soalnya saya pernah baca di buku fatwa-fatwa kontemporer Yusuf Qordowi kalau orang pernah meninggalkan puasa pada tahun-tahun yang lalu itu harus tetep di bayar karena termasuk hutang. Bagaimana korelasinya dengan peleburan dosa yang diakibatkan melakukan puasa haji tersebut?
Atas jawabannya saya sampaikan terimakasih
wassalamualaikum wr.wb
Jawaban:
Wa’alaikum salam wr.wb.
Terima kasih atas pertanyaan sangat luar biasa ini.
Jawaban dari pertanyaan pertama: Terlebih dahulu, mari kita lihat pendapat para ulama seputar hukum membaca doa iftitah dalam shalat. Jumhur ulama yaitu Hanafiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa disunnatkan membaca doa iftitah setelah Takbiratul Ihram pada rakaat pertama. Hadits jumhur sangat banyak.
Sedangkan menurut Malikiyyah, membaca doa iftitah dalam shalat hukumnya makruh. Malikiyyah berhujjah dengan hadits Bukhari Muslim, di antaranya, yang menegaskan bahwa Rasulullah saw memulai shalatnya dengan langsung membaca surat al-Fatihah, tanpa membaca doa iftitah terlebih dahulu. Hadits dimaksud adalah:
Terima kasih atas pertanyaan sangat luar biasa ini.
Jawaban dari pertanyaan pertama: Terlebih dahulu, mari kita lihat pendapat para ulama seputar hukum membaca doa iftitah dalam shalat. Jumhur ulama yaitu Hanafiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa disunnatkan membaca doa iftitah setelah Takbiratul Ihram pada rakaat pertama. Hadits jumhur sangat banyak.
Sedangkan menurut Malikiyyah, membaca doa iftitah dalam shalat hukumnya makruh. Malikiyyah berhujjah dengan hadits Bukhari Muslim, di antaranya, yang menegaskan bahwa Rasulullah saw memulai shalatnya dengan langsung membaca surat al-Fatihah, tanpa membaca doa iftitah terlebih dahulu. Hadits dimaksud adalah:
عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين)) [متفق عليه]
Artinya: “Anas bin Malik berkata: “Rasulullah saw, Abu Bakar dan Umar memulai shalat dengan membaca surat al-Fatihah” (HR. Bukhari Muslim).
Jumhur ulama kemudian berbeda pendapat ketika imam telah atau sedang membaca surat al-Fatihah atau surat dengan suara keras ataupun tidak (shalat yang dikeraskan bacaan imamnya ataupun dipelankan), apakah makmum disunnatkan membaca doa iftitah?
Menurut Hanafiyyah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Badâi’ as-Shanâi’, jika imam telah membaca al-Fatihah atau yang lainnya, baik dalam shalat yang dinyaringkan bacaan imamnya ataupun dipelankan, maka makmum tidak dianjurkan membaca doa Iftitah, baik makmum tersebut posisinya sebagai masbuk atau tidak. Hal ini dikarenakan mendengarkan bacaan al-Qur’an dalam shalat yang dikeraskan bacaannya hukumnya wajib, sebagaimana firman Allah:
Jumhur ulama kemudian berbeda pendapat ketika imam telah atau sedang membaca surat al-Fatihah atau surat dengan suara keras ataupun tidak (shalat yang dikeraskan bacaan imamnya ataupun dipelankan), apakah makmum disunnatkan membaca doa iftitah?
Menurut Hanafiyyah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Badâi’ as-Shanâi’, jika imam telah membaca al-Fatihah atau yang lainnya, baik dalam shalat yang dinyaringkan bacaan imamnya ataupun dipelankan, maka makmum tidak dianjurkan membaca doa Iftitah, baik makmum tersebut posisinya sebagai masbuk atau tidak. Hal ini dikarenakan mendengarkan bacaan al-Qur’an dalam shalat yang dikeraskan bacaannya hukumnya wajib, sebagaimana firman Allah:
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
Artinya: “Dan apabila dibacakan Al Quran, Maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat” (QS. Al-Araf: 204).
Sementara membaca doa iftitah hukumnya sunnat. Maka yang wajib harus didahulukan dari pada yang sunnat. Demikian juga dengan shalat yang dipelankan bacaan imamnya, tetap tidak dianjurkan membaca doa iftitah, karena menurut Hanafiyyah, bacaan imam adalah bacaan makmum juga. Maksudnya, dengan imam membaca doa iftitah, maka dipandang sebagai bacaan untuk makmum juga.
Adapun menurut Hanabilah, dalam shalat yang dipelankan bacaannya, makmum dianjurkan membaca doa iftitah juga ta’udz (yaitu bacaan a’ûdzu billâhi minas syaithânirrajîm). Adapun dalam shalat yang dikeraskan bacaan imamnya, dalam Madzhab Hanbali terdapat dua riwayat sebagaimana disampaikan Ibnu Qudamah dalam al-Mughni. Riwayat pertama, makmum membaca doa iftitah dan ta’udz pada saat imam sedang berhenti sejenak tidak membaca. Jika waktu berhenti imam tersebut hanya cukup untuk membaca doa iftitah saja tanpa ta’udz, maka makmum dianjurkan hanya membaca doa iftitah saja, dan tidak ta’udz.
Namun jika imam tidak berhenti dan terus membaca dengan suara nyaring, maka makmum tidak membaca doa iftitah juga tidak membaca ta’udz, tapi memperhatikan bacaan imam.
Dalam riwayat kedua disebutkan, dalam shalat yang dinyaringkan pun, makmum tetap disunnatkan membaca doa iftitah dan ta’udz. Karena bacaan imam adalah bacaan makmum juga kecuali membaca doa iftitah dan ta’udz.
Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i, disunnatkan membaca doa iftitah dalam shalat wajib ataupun sunnat, baik dalam shalat berjamaah ataupun sendiri, baik untuk imam ataupun makmum, baik shalat yang dikeraskan bacaan imamnya ataupun yang dipelankan. Bahkan, sekalipun imam sudah membaca surat al-Fatihah atau membaca amiin, makmum tetap disunnatkan membaca doa iftitah.
Kecuali apabila makmum telah membaca ta’udz atau surat al-Fatihah, sekalipun membacanya itu karena lupa atau tidak sengaja, maka dalam keadaan demikian tidak disunnatkan membaca doa iftitah. Demikian juga, apabila makmum merasa cukup waktu untuk dapat membaca surat al-Fatihah. Adapun jika makmum merasa khawatir apabila membaca doa iftitah waktunya tidak akan cukup untuk membaca surat al-Fatihah, maka dalam keadaan demikian tidak disunnatkan baginya membaca doa iftitah, tapi langsung membaca surat al-Fatihah saja.
Imam Nawawi dalam al-Majmû’ mengatakan:
Sementara membaca doa iftitah hukumnya sunnat. Maka yang wajib harus didahulukan dari pada yang sunnat. Demikian juga dengan shalat yang dipelankan bacaan imamnya, tetap tidak dianjurkan membaca doa iftitah, karena menurut Hanafiyyah, bacaan imam adalah bacaan makmum juga. Maksudnya, dengan imam membaca doa iftitah, maka dipandang sebagai bacaan untuk makmum juga.
Adapun menurut Hanabilah, dalam shalat yang dipelankan bacaannya, makmum dianjurkan membaca doa iftitah juga ta’udz (yaitu bacaan a’ûdzu billâhi minas syaithânirrajîm). Adapun dalam shalat yang dikeraskan bacaan imamnya, dalam Madzhab Hanbali terdapat dua riwayat sebagaimana disampaikan Ibnu Qudamah dalam al-Mughni. Riwayat pertama, makmum membaca doa iftitah dan ta’udz pada saat imam sedang berhenti sejenak tidak membaca. Jika waktu berhenti imam tersebut hanya cukup untuk membaca doa iftitah saja tanpa ta’udz, maka makmum dianjurkan hanya membaca doa iftitah saja, dan tidak ta’udz.
Namun jika imam tidak berhenti dan terus membaca dengan suara nyaring, maka makmum tidak membaca doa iftitah juga tidak membaca ta’udz, tapi memperhatikan bacaan imam.
Dalam riwayat kedua disebutkan, dalam shalat yang dinyaringkan pun, makmum tetap disunnatkan membaca doa iftitah dan ta’udz. Karena bacaan imam adalah bacaan makmum juga kecuali membaca doa iftitah dan ta’udz.
Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i, disunnatkan membaca doa iftitah dalam shalat wajib ataupun sunnat, baik dalam shalat berjamaah ataupun sendiri, baik untuk imam ataupun makmum, baik shalat yang dikeraskan bacaan imamnya ataupun yang dipelankan. Bahkan, sekalipun imam sudah membaca surat al-Fatihah atau membaca amiin, makmum tetap disunnatkan membaca doa iftitah.
Kecuali apabila makmum telah membaca ta’udz atau surat al-Fatihah, sekalipun membacanya itu karena lupa atau tidak sengaja, maka dalam keadaan demikian tidak disunnatkan membaca doa iftitah. Demikian juga, apabila makmum merasa cukup waktu untuk dapat membaca surat al-Fatihah. Adapun jika makmum merasa khawatir apabila membaca doa iftitah waktunya tidak akan cukup untuk membaca surat al-Fatihah, maka dalam keadaan demikian tidak disunnatkan baginya membaca doa iftitah, tapi langsung membaca surat al-Fatihah saja.
Imam Nawawi dalam al-Majmû’ mengatakan:
قال اصحابنا: إذا حضر مسبوق فوجد الإمام في القراءة وخاف ركوعه قبل فراغه من الفاتحة، فينبغي أن لا يقول دعاء الافتتاح والتعوذ، بل يبادر الي الفاتحة، لما ذكره المصنف. وإن غلب على ظنه أنه إذا قال الدعاء والتعوذ أدرك تمام الفاتحة، استحب الاتيان بهما.
فلو ركع الامام وهو في أثناء الفاتحة فثلاثة أوجه: (أحدها) يتم الفاتحة (والثاني) يركع ويسقط عنه قراءتها، ودليلهما ما ذكره المصنف، قال البندنيجى: هذا الثاني هو نصه في الاملاء، قال: وهو المذهب (والثالث) وهو الاصح وهو قول الشيخ أبى زيد المروزى وصححه القفال والمعتبرون، أنه إن لم يقل شيئا من دعاء الافتتاح والتعوذ ركع وسقط عنه بقية الفاتحة، وان قال شيئا من ذلك لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدره لتقصيره بالتشاغل، فان قلنا: عليه اتمام الفاتحة فتخلف ليقرأ كان متخلفا بعذر، فيسعي خلف الامام على نظم صلاة نفسه، فيتم القراءة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد حتى يلحق الامام، ويعذر في التخلف بثلاثة أركان مقصودة، وتحسب له ركعته.
Artinya: “Para ulama dalam madzhab kami (Madzhab Syafi’i) berkata: “Jika masbuk mendapatkan imam sedang membaca bacaan, dan ia khawatir sebelum ia selesai membaca surat al-Fatihah imam akan ruku, maka hendaknya ia tidak membaca surat al-Fatihah juga ta’udz. Akan tetapi ia segera membaca surat al-Fatihah, sebagaimana disebutkan oleh pengarang (maksudnya Imam asy-Syairazi pengarang kitab al-Muhadzdzab=pent).
Namun jika menurut dugaan kuatnya jika membaca doa iftitah dan ta’udz dapat juga membaca surat al-Fatihah secara lengkap, maka disunnatkan baginya untuk membaca doa iftitah dan ta’udz.
Namun apabila imam kemudian ruku’, sementara ia masih membaca surat al-Fatihah, maka dalam hal ini ada tiga pendapat para ulama Syafi’iyyah. Pendapat pertama, hendaknya ia meneruskan membaca surat al-Fatihah. Pendapat kedua, hendaknya ia ikut ruku bersama imam, dan gugur kewajibannya membaca surat al-Fatihah. Dalilnya sebagaimana disebutkan oleh pengarang. Imam al-Bandaniji mengatakan: pendapat kedua ini sebagaimana yang tertulis dalam kitab al-Imlâ`, dan ini merupakan pendapat kuat dalam Madzhab Syafi’i.
Pendapat ketiga, dan ini merupakan pendapat yang paling kuat, yang merupakan pendapatnya Syaikh Abu Zaid al-Marwazy, juga dikuatkan oleh al-Qaffal dan lainnya, jika ia belum membaca sedikitpun dari doa iftitah dan ta’udz, maka hendaknya ia langsung ruku, dan gugur kewajiban membaca sisa ayat dari surat al-Fatihahnya.
Jika ia telah membaca bacaan doa iftitah atau ta’udz sekalipun sedikit, maka ia harus membaca surat al-Fatihah sekemampuannya, sekalipun tidak seluruhnya. Namun apabila kita mewajibkannya untuk membaca surat al-Fatihah seluruhnya, kemudian ia menjadi tertinggal dari imam, maka tertinggalnya itu dipandang karena ada udzur. Ia hendaknya melakukan gerakan shalatnya sendiri sesuai dengan yang tertinggalnya itu, sampai ia dapat menyelesaikan seluruh ayat dari surat al-Fatihah, lalu ruku, kemudian i’tidal, kemudian sujud sampai ia mendapatkan gerakan imam. Dipandang tidak mengapa dalam keadaan seperti itu, ia tertinggal sampai tiga gerakan rukun tersebut, dan tetap dipandang ia telah mendapatkan satu rakaat”.
Demikian, penulis sengaja lebih memperpanjang penjelasan dalam Madzhab Syafi’i, mengingat kebanyakan dari masyarakat Indonesia bermadzhabkan Syafi’i.
Namun, saya secara pribadi, lebih condong untuk mengambil pendapat, bahwa jika imam dikeraskan bacaannya, maka kita hanya mendengarkan bacaan imam saja, dan tidak perlu membaca doa iftitah. Mengingat bacaan iftitah hukumnya sunnat bukan termasuk rukun.
Adapun membaca surat al-Fatihah, hemat penulis, tetap dibaca sekalipun imam dikeraskan suara bacaannya, sebagai wujud kehati-hatian, di samping lebih selamat dan keluar dari perdebatan para ulama. Demikian, wallâhu a’lam bis shawâb.
Namun jika menurut dugaan kuatnya jika membaca doa iftitah dan ta’udz dapat juga membaca surat al-Fatihah secara lengkap, maka disunnatkan baginya untuk membaca doa iftitah dan ta’udz.
Namun apabila imam kemudian ruku’, sementara ia masih membaca surat al-Fatihah, maka dalam hal ini ada tiga pendapat para ulama Syafi’iyyah. Pendapat pertama, hendaknya ia meneruskan membaca surat al-Fatihah. Pendapat kedua, hendaknya ia ikut ruku bersama imam, dan gugur kewajibannya membaca surat al-Fatihah. Dalilnya sebagaimana disebutkan oleh pengarang. Imam al-Bandaniji mengatakan: pendapat kedua ini sebagaimana yang tertulis dalam kitab al-Imlâ`, dan ini merupakan pendapat kuat dalam Madzhab Syafi’i.
Pendapat ketiga, dan ini merupakan pendapat yang paling kuat, yang merupakan pendapatnya Syaikh Abu Zaid al-Marwazy, juga dikuatkan oleh al-Qaffal dan lainnya, jika ia belum membaca sedikitpun dari doa iftitah dan ta’udz, maka hendaknya ia langsung ruku, dan gugur kewajiban membaca sisa ayat dari surat al-Fatihahnya.
Jika ia telah membaca bacaan doa iftitah atau ta’udz sekalipun sedikit, maka ia harus membaca surat al-Fatihah sekemampuannya, sekalipun tidak seluruhnya. Namun apabila kita mewajibkannya untuk membaca surat al-Fatihah seluruhnya, kemudian ia menjadi tertinggal dari imam, maka tertinggalnya itu dipandang karena ada udzur. Ia hendaknya melakukan gerakan shalatnya sendiri sesuai dengan yang tertinggalnya itu, sampai ia dapat menyelesaikan seluruh ayat dari surat al-Fatihah, lalu ruku, kemudian i’tidal, kemudian sujud sampai ia mendapatkan gerakan imam. Dipandang tidak mengapa dalam keadaan seperti itu, ia tertinggal sampai tiga gerakan rukun tersebut, dan tetap dipandang ia telah mendapatkan satu rakaat”.
Demikian, penulis sengaja lebih memperpanjang penjelasan dalam Madzhab Syafi’i, mengingat kebanyakan dari masyarakat Indonesia bermadzhabkan Syafi’i.
Namun, saya secara pribadi, lebih condong untuk mengambil pendapat, bahwa jika imam dikeraskan bacaannya, maka kita hanya mendengarkan bacaan imam saja, dan tidak perlu membaca doa iftitah. Mengingat bacaan iftitah hukumnya sunnat bukan termasuk rukun.
Adapun membaca surat al-Fatihah, hemat penulis, tetap dibaca sekalipun imam dikeraskan suara bacaannya, sebagai wujud kehati-hatian, di samping lebih selamat dan keluar dari perdebatan para ulama. Demikian, wallâhu a’lam bis shawâb.
Jawaban dari pertanyaan kedua:
Betul sekali, banyak hadits yang menjelaskan amal-amal ibadah tertentu dapat menghapus dosa yang telah lalu. Namun, para ulama mengatakan bahwa dosa-dosa dimaksud adalah dosa-dosa kecil atau yang sering disebut dengan al-khathî’ah, kesalahan, bukan dosa-dosa besar.
Untuk dosa besar, seseorang harus bertaubat dengan sebenar-benarnya, dan tidak mengulangi perbuatan serupa. Jika dosanya itu berkaitan dengan hak manusia, maka hak-hak itu harus ditunaikan terlebih dahulu. Misalnya, jika ia mencuri, korupsi, maka barang yang dikorupsi dan dicuri itu harus dikembalikan kepada pemiliknya terlebih dahulu. Jika belum dilakukan demikian, maka taubatnya dipandang belum sempurna, dan bahkan menurut sebagian ulama, Allah tidak akan menerima taubatnya sebelum ia mengembalikan hak-hak manusia tersebut.
Sekali lagi perlu saya tegaskan, maksud dosa-dosa yang akan diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar perlu bertaubat dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, jika berkaitan dengan hak manusia. Karena itu salah besar mereka yang mempunyai pemahaman, dia korupsi di mana-mana, kemudian ia naik haji, dengan anggapan, dosa kurupsinya gugur dan sudah diampuni. Ini sangat tidak benar. Dalam pengampunan dosa dan tobat ada aturan-aturan yang di antaranya telah saya sampaikan di atas.
Kemudian menyangkut masalah fatwa Syaikh Qaradhawi tentang wajibnya mengqadha shalat wajib yang ditinggalkan sengaja pada tahun-tahun lalu, para ulama dalam hal ini terbagi dua pendapat.
Pendapat pertama mengatakan, bahwa orang yang meninggalkan shalat wajib pada tahun-tahun sebelumnya, begitu dia sadar dan taubat, maka di samping ia bertaubat kepada Allah, ia juga wajib mengqadha seluruh shalat wajib yang telah ditinggalkannya itu sekalipun jumlah shalat yang ditinggalkannya sangat banyak. Pendapat ini adalah pendapat Jumhur ulama, termasuk pendapatnya empat madzhab Fiqih, juga yang lainnya.
Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya al-Majmû’ mengatakan bahwa wajibnya mengqadha ini sudah merupakan Ijma para ulama. Berikut ini perkataan Imam Nawawi:
Untuk dosa besar, seseorang harus bertaubat dengan sebenar-benarnya, dan tidak mengulangi perbuatan serupa. Jika dosanya itu berkaitan dengan hak manusia, maka hak-hak itu harus ditunaikan terlebih dahulu. Misalnya, jika ia mencuri, korupsi, maka barang yang dikorupsi dan dicuri itu harus dikembalikan kepada pemiliknya terlebih dahulu. Jika belum dilakukan demikian, maka taubatnya dipandang belum sempurna, dan bahkan menurut sebagian ulama, Allah tidak akan menerima taubatnya sebelum ia mengembalikan hak-hak manusia tersebut.
Sekali lagi perlu saya tegaskan, maksud dosa-dosa yang akan diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar perlu bertaubat dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, jika berkaitan dengan hak manusia. Karena itu salah besar mereka yang mempunyai pemahaman, dia korupsi di mana-mana, kemudian ia naik haji, dengan anggapan, dosa kurupsinya gugur dan sudah diampuni. Ini sangat tidak benar. Dalam pengampunan dosa dan tobat ada aturan-aturan yang di antaranya telah saya sampaikan di atas.
Kemudian menyangkut masalah fatwa Syaikh Qaradhawi tentang wajibnya mengqadha shalat wajib yang ditinggalkan sengaja pada tahun-tahun lalu, para ulama dalam hal ini terbagi dua pendapat.
Pendapat pertama mengatakan, bahwa orang yang meninggalkan shalat wajib pada tahun-tahun sebelumnya, begitu dia sadar dan taubat, maka di samping ia bertaubat kepada Allah, ia juga wajib mengqadha seluruh shalat wajib yang telah ditinggalkannya itu sekalipun jumlah shalat yang ditinggalkannya sangat banyak. Pendapat ini adalah pendapat Jumhur ulama, termasuk pendapatnya empat madzhab Fiqih, juga yang lainnya.
Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya al-Majmû’ mengatakan bahwa wajibnya mengqadha ini sudah merupakan Ijma para ulama. Berikut ini perkataan Imam Nawawi:
أجمع العلماء الذين يعتد بهم علي أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها، وخالفهم أبو محمد على ابن حزم، فقال: لا يقدر علي قضائها ابدا، ولا يصح فعلها ابدا، قال: بل يكثر من فعل الخير، وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة، ويستغفر الله تعالي ويتوب، وهذا الذى قاله، مع أنه مخالف للاجماع، باطل من جهة الدليل، وبسط هو الكلام في الاستدلال له، وليس فيما ذكر دلالة أصلا
Artinya: “Para ulama yang pendapatnya diperhitungkan telah sepakat bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, wajib mengqadha shalatnya itu. Abu Muhammad Ali bin Hazm (yaitu Ibn Hazm=pent) berpendapat lain. Menurutnya, ia tidak diwajibkan mengqadha shalat selamanya, dan praktek ibadah qadhanya juga tidak sah untuk selamanya. Ia juga berkata: ‘Hendaknya ia memperbanyak melakukan kebaikan, dan shalat sunnat untuk lebih memberatkan timbangan kebaikannya kelak di hari Kiamat, juga memohon ampun kepada Allah dan bertaubat”. Ini perkataanya. Sekalipun pendapat Ibnu Hazm ini menyalahi Ijma para ulama, dan pendapat ini batal dari sisi dalil. Ibnu Hazm juga panjang lebar menjelaskan pendapatnya ini, hanya saja dari penjelasan dan pendapatnya ini tidak ada dalil yang khusus dan valid”.
Dalam kesempatan lain, Imam Nawawi lebih keras lagi, beliau mengatakan pendapat Ibnu Hazm di atas adalah pendapat yang salah dan bodoh. Dalam Syarah nya terhadap Shahih Muslim, Imam Nawawi berkata:
Dalam kesempatan lain, Imam Nawawi lebih keras lagi, beliau mengatakan pendapat Ibnu Hazm di atas adalah pendapat yang salah dan bodoh. Dalam Syarah nya terhadap Shahih Muslim, Imam Nawawi berkata:
وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، …. وهذا خطأ من قائله وجهالة
Artinya: “Sebagian zhahiriyyah berpendapat yang sangat ganjil: ‘Tidak wajib mengqadha shalat yang ditinggalkan tanpa udzur”. …Ini adalah kesalahan dan kebodohan dari yang mengatakannya”.
Di antara dalil jumhur ulama dalam hal ini adalah hadits berikut ini:
Di antara dalil jumhur ulama dalam hal ini adalah hadits berikut ini:
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوما مع الكفارة، أي بدل اليوم الذى أفسده بالجماع عمدا [رواه البيهقى باسناد جيد أبو داود]
Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah saw memerintahkan orang yang berhubungan badan pada siang hari di bulan Ramadhan untuk berpuasa satu hari berikut membayar kifarat, yaitu sebagai ganti dari hari yang dirusaknya itu melalui berhubungan badan secara sengaja” (HR. Baihaki, juga Abu Daud dengan sanad bagus).
Di samping itu, Jumhur juga berhujjah jika orang yang lupa tidak shalat dalam hadits diwajibkan untuk mengqadha shalatnya, maka apalagi orang yang sengaja meninggalkan shalat.
Pendapat kedua, mengatakan ia tidak diperbolehkan mengqadha shalat-shalat yang ditinggalkan tersebut, akan tetapi ia harus bertaubat dengan sebenar-benarnya di samping ia harus memperbanyak berbuat kebaikan, shalat sunnat dan istighfar juga bertaubat. Pendapat ini adalah pendapatnya Ibnu Hazm, juga Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah termasuk Syaikh bin Baz.
Di antara dalilnya adalah bahwa taubat dengan sebenarnya dapat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, seperti dalam firman Allah berikut ini:
Di samping itu, Jumhur juga berhujjah jika orang yang lupa tidak shalat dalam hadits diwajibkan untuk mengqadha shalatnya, maka apalagi orang yang sengaja meninggalkan shalat.
Pendapat kedua, mengatakan ia tidak diperbolehkan mengqadha shalat-shalat yang ditinggalkan tersebut, akan tetapi ia harus bertaubat dengan sebenar-benarnya di samping ia harus memperbanyak berbuat kebaikan, shalat sunnat dan istighfar juga bertaubat. Pendapat ini adalah pendapatnya Ibnu Hazm, juga Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah termasuk Syaikh bin Baz.
Di antara dalilnya adalah bahwa taubat dengan sebenarnya dapat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, seperti dalam firman Allah berikut ini:
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
Artinya: “Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Az-Zumar: 53).
Demikian juga dengan ayat-ayat dan hadits-hadits lain yang menjelaskan bahwa taubat dapat menghapus dosa-dosa telah lalu.
Di samping itu, pendapat ini juga berargumen, sebagaimana disampaikan oleh Syaikh bin Baz dalam Fatâwâ nya, banyak orang yang masuk Islam pada masa Fathu Mekkah, namun Rasulullah saw tidak memerintahkan mereka untuk mengqadha satupun kewajiban Islam yang ditinggalkannya. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat pada masa khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ketika banyak orang Arab dari Bani Hunaifah dan lainnya yang murtad setelah Rasulullah saw wafat, kemudian mereka masuk Islam kembali dan bertaubat kepada Allah. Namun para sahabat tidak memerintahkan mereka untuk mengqodha shalat, juga puasa yang ditinggalkannya. Dengan demikian, mengqadha shalat atau puasa yang ditinggalkan tidak wajib.
Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah mewajibkan orang tersebut untuk memperbanyak taubat, istighfar, berbuat kebaikan dan memperbanyak melaksanakan shalat sunnat. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membahas persoalan ini secara panjang lebar dalam kitabnya ash-Shalâh wa Hukm Târikihâ.
Apabila membandingkan kedua pendapat di atas berikut dalil-dalil yang dikemukakan dalam masing-masing kitab mereka, hemat saya, pendapat jumhur lebih kuat dan lebih hati-hati. Dengan demikian, saya secara pribadi mengikuti pendapat Jumhur ulama termasuk mengikuti pendapatnya Syaikh Qaradhawi dan ulama-ulama lainnya, akan wajibnya mengqadha shalat yang ditinggalkan dengan sengaja pada tahun-tahun sebelumnya. Terlebih, Imam Nawawi menilainya telah terjadi ijma’ para ulama dalam hal ini. Dan memang terbukti. Hemat saya, tidak ada ulama lain, selain sebagian Zhahiriyyah termasuk Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim, yang tidak mewajibkan mengqadha shalat dimaksud.
Kini, mari kita bahas bagaimana cara mengqadhanya. Pertama, shalat yang ditinggalkan dengan sengaja, menurut Madzhab Syafi’i wajib diqadha segera (fauran). Selain itu, empat madzhab fiqih juga sepakat bahwa shalat yang diqadha tersebut boleh dilakukan dalam semua waktu, sekalipun dalam waktu makruh, seperti ketika matahari terbit atau terbenam.
Dalam kitab ar-Raud al-Murbi’ karya Imam al-Buhûty al-Hanbali disebutkan:
Demikian juga dengan ayat-ayat dan hadits-hadits lain yang menjelaskan bahwa taubat dapat menghapus dosa-dosa telah lalu.
Di samping itu, pendapat ini juga berargumen, sebagaimana disampaikan oleh Syaikh bin Baz dalam Fatâwâ nya, banyak orang yang masuk Islam pada masa Fathu Mekkah, namun Rasulullah saw tidak memerintahkan mereka untuk mengqadha satupun kewajiban Islam yang ditinggalkannya. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat pada masa khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ketika banyak orang Arab dari Bani Hunaifah dan lainnya yang murtad setelah Rasulullah saw wafat, kemudian mereka masuk Islam kembali dan bertaubat kepada Allah. Namun para sahabat tidak memerintahkan mereka untuk mengqodha shalat, juga puasa yang ditinggalkannya. Dengan demikian, mengqadha shalat atau puasa yang ditinggalkan tidak wajib.
Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah mewajibkan orang tersebut untuk memperbanyak taubat, istighfar, berbuat kebaikan dan memperbanyak melaksanakan shalat sunnat. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membahas persoalan ini secara panjang lebar dalam kitabnya ash-Shalâh wa Hukm Târikihâ.
Apabila membandingkan kedua pendapat di atas berikut dalil-dalil yang dikemukakan dalam masing-masing kitab mereka, hemat saya, pendapat jumhur lebih kuat dan lebih hati-hati. Dengan demikian, saya secara pribadi mengikuti pendapat Jumhur ulama termasuk mengikuti pendapatnya Syaikh Qaradhawi dan ulama-ulama lainnya, akan wajibnya mengqadha shalat yang ditinggalkan dengan sengaja pada tahun-tahun sebelumnya. Terlebih, Imam Nawawi menilainya telah terjadi ijma’ para ulama dalam hal ini. Dan memang terbukti. Hemat saya, tidak ada ulama lain, selain sebagian Zhahiriyyah termasuk Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim, yang tidak mewajibkan mengqadha shalat dimaksud.
Kini, mari kita bahas bagaimana cara mengqadhanya. Pertama, shalat yang ditinggalkan dengan sengaja, menurut Madzhab Syafi’i wajib diqadha segera (fauran). Selain itu, empat madzhab fiqih juga sepakat bahwa shalat yang diqadha tersebut boleh dilakukan dalam semua waktu, sekalipun dalam waktu makruh, seperti ketika matahari terbit atau terbenam.
Dalam kitab ar-Raud al-Murbi’ karya Imam al-Buhûty al-Hanbali disebutkan:
يجوز قضاء الفرائض فيها أي في وقت النهي كلها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متفق عليه
Artinya: “Mengqadha shalat-shalat wajib boleh dilakukan pada seluruh waktu yang dilarang. Hal ini berdasarkan keumuman hadits: “Siapa yang tidak shalat karena tertidur atau lupa, maka hendaknya ia shalat manakala ia ingat” (Muttafaq ‘alaih).
Di samping itu, dalam hal cara mengqadhanya ia dapat melakukan berapa shalat pun dalam sehari, menurut kemampuannya dan selama tidak mengganggu kegiatan sehari-harinya. Misalnya dalam sehari ia mengqadha untuk tiga hari, berarti 15 kali shalat, atau hanya mengqadha satu hari. Semua terserah yang bersangkutan, berapa shalat yang dapat dilakukannya dalam sehari semalam.
Lalu bagaimana kalau dia tidak ingat berapa tahun yang persisnya ia tidak melakukan shalat? Maka jumhur ulama dalam hal ini mengatakan ia perlu memperkirakan berapa lama kira-kira ia tidak melakukannya. Jika tidak tahu juga, maka lakukanlah qadha shalat dalam jumlah yang dapat menenangkan hati. Dengan kata lain berdasarkan perkiraan yang paling menenangkan.
Lalu apakah dalam melaksanakannya harus tertib seperti urutan shalat, yaitu zhuhur dulu, baru azhar, baru maghrib dan seterusnya? Menurut Malikiyyah, tertib dalam melakukannya adalah wajib, tapi tidak termasuk syarat sah qadha.
Sedangkan menurut Hanabilah, tertib dalam melaksanakan urutan shalat adalah wajib, dan termasuk syarat sah shalat, kecuali karena udzur. Dalam kitab Mathâlib Ulin Nuhâ, salah satu kitab fiqih dalam Madzhab Hanbali disebutkan:
Di samping itu, dalam hal cara mengqadhanya ia dapat melakukan berapa shalat pun dalam sehari, menurut kemampuannya dan selama tidak mengganggu kegiatan sehari-harinya. Misalnya dalam sehari ia mengqadha untuk tiga hari, berarti 15 kali shalat, atau hanya mengqadha satu hari. Semua terserah yang bersangkutan, berapa shalat yang dapat dilakukannya dalam sehari semalam.
Lalu bagaimana kalau dia tidak ingat berapa tahun yang persisnya ia tidak melakukan shalat? Maka jumhur ulama dalam hal ini mengatakan ia perlu memperkirakan berapa lama kira-kira ia tidak melakukannya. Jika tidak tahu juga, maka lakukanlah qadha shalat dalam jumlah yang dapat menenangkan hati. Dengan kata lain berdasarkan perkiraan yang paling menenangkan.
Lalu apakah dalam melaksanakannya harus tertib seperti urutan shalat, yaitu zhuhur dulu, baru azhar, baru maghrib dan seterusnya? Menurut Malikiyyah, tertib dalam melakukannya adalah wajib, tapi tidak termasuk syarat sah qadha.
Sedangkan menurut Hanabilah, tertib dalam melaksanakan urutan shalat adalah wajib, dan termasuk syarat sah shalat, kecuali karena udzur. Dalam kitab Mathâlib Ulin Nuhâ, salah satu kitab fiqih dalam Madzhab Hanbali disebutkan:
ويجب على مكلف لا مانع به قضاء مكتوبة فائتة من الخمس مرتبا …. فإن ترك ترتيبها بلا عذر لم يصح لأنه شرط كترتيب الركوع والسجود
Artinya: “Mukallaf tanpa penghalang wajib mengqadha shalat wajib yang ditinggalkan secara tertib. Jika ia melakukannya tidak dengan tertib, tanpa ada udzur, maka tidak sah, karena tertib adalah syarat sah shalat, sebagaimana tertibnya urutan ruku dan sujud”.
Sedangkan menurut Syafi’iyyah, tertib hukumnya sunnat saja. Syaikh Zakariya al-Anshari dalam kitabnya Asnal Mathalib mengatakan:
Sedangkan menurut Syafi’iyyah, tertib hukumnya sunnat saja. Syaikh Zakariya al-Anshari dalam kitabnya Asnal Mathalib mengatakan:
ويجب قضاء الفوائت الفرائض بخبر الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ثم إن فاتت بغير عذر وجب قضاؤها على الفور، وإلا ندب ويستحب ترتيبها لترتيبه صلى الله عليه وسلم فوائت الخندق وخروجا من الخلاف
Artinya: “Wajib mengqadha shalat wajib yang ditinggalkan, berdasarkan hadits Bukhari Muslim: “Siapa yang tidak shalat karena tertidur, atau lupa, maka hendaknya ia shalat ketika ia ingat”. Kemudian jika ia meninggalkannya dengan sengaja, tanpa udzur, maka wajib mengqadhanya segera. Jika tidak sengaja, sunnat mengqadhanya segera. Juga disunnatkan dalam melaksanakannya secara tertib, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw ketika mengqadha shalat yang tertinggal di Khandak, beliau melakukannya secara tertib, di samping sebagai upaya keluar dari perbedaan pendapat para ulama”.
Termasuk juga mengqadha shalat yang ditinggalkan boleh dilakukan secara berjamaah. Dalam kitab al-Majmû’, Imam Nawawi berkata:
Termasuk juga mengqadha shalat yang ditinggalkan boleh dilakukan secara berjamaah. Dalam kitab al-Majmû’, Imam Nawawi berkata:
وأما المقضية من المكتوبات فليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية بلا خلاف، ولكن يستحب الجماعة في المقضية التي يتفق الإمام والمأموم فيها بأن يفوتهما ظهر أو عصر، ودليله الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فاتته هو وأصحابه صلاة الصبح صلاها بهم جماعة. قال القاضي عياض في شرح مسلم: لا خلاف بين العلماء في جواز الجماعة في القضاء إلا ما حكي عن الليث بن سعد من منع ذلك، وهذا المنقول عن الليث إن صح عنه مردود بالأحاديث الصحيحة وإجماع من قبله. وأما القضاء خلف الأداء والأداء خلف القضاء وقضاء صلاة خلف من يقضي غيرها فكله جائز عندنا إلا أن الانفراد بها أفضل للخروج من خلاف العلماء
Artinya: “Adapun mengqadha shalat-shalat wajib, maka tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa berjamaah bukanlah fardu ain atau fardhu kifayah. Akan tetapi disunnatkan dilakukan secara berjamaah yang mana antara imam dan makmun sama shalatnya, misalnya sama-sama ZHuhur atau Ashar. Dalilnya adalah hadits-hadits shahih bahwa ketika Rasulullah saw dan para sahabatnya tertinggal shalat Shubuh, beliau dan para sahabat melakukannya secara berjamaah. Qadhi Iyad dalam Syarh Muslim berkata: “Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, bolehnya berjamaah dalam mengqadha shalat, kecuali yang diriwayatkan dari Imam Laits bin Sa’ad yang melarang hal itu. Riwayat ini, jika benar dari Imam Laits, maka tertolak karena bertentangan dengan hadits-hadits shahih dan Ijma’ para ulama sebelumnya. Adapun mengqadha shalat di belakang orang yang melakukannya tepat pada waktunya, atau orang yang tepat waktu di belakang orang yang mengqadha, atau yang mengqadha di belakang yang mengqadha lainnya, dalam madzhab kami, semuanya boleh. Hanya saja, jika ia shalat sendiri lebih baik baginya, sebagai upaya menghindari perbedaan pendapat para ulama”.
Demikian seputar bahasan mengqadha shalat yang ditinggalkan dengan sengaja, semoga bermanfaat. Wallâhu a’lam bis shawâb. Aep SD
Demikian seputar bahasan mengqadha shalat yang ditinggalkan dengan sengaja, semoga bermanfaat. Wallâhu a’lam bis shawâb. Aep SD


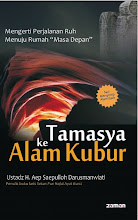




0 komentar:
Post a Comment